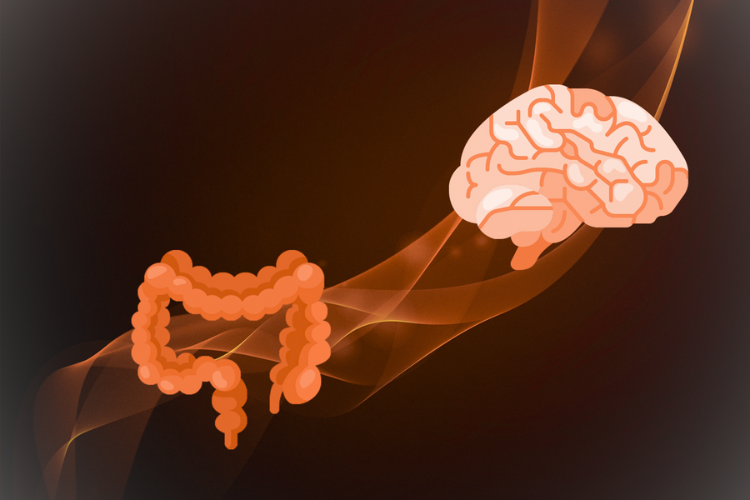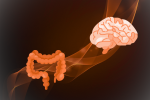Ia perempuan yang luar biasa. Lewat perusahaannya Thisable Enterprise, ia telah membantu ribuan orang agar bisa mengembangkan diri, bekerja dan dihargai. “Kira-kira sudah 3000 orang yang kami bantu lewat workshop, creative center, dan cara bekerja dan berkomunikasi di perusahaan. Kami menyediakan tenaga kerja yang disesuaikan kebutuhan perusahaan,” ujar Angkie Yudistia, Founder dan CEO Thisable Enterprise.
Salah satu perusahaan pengguna jasa Angkie adalah Gojek. Karyawan yang disalurkan Angkie tidak hanya disalurkan pengojek online, tapi juga di bisnis unitnya seperti Go-Massage (pijat), Go-Clean (bebersih) dan Go-Glam (rias). Tantangan terbesar, menurut Angkie, adalah bagaimana orang-orang yang dia salurkan memiliki rasa percaya diri. Tahap selanjutnya adalah membuat orang lain percaya pada karyawan yang dia salurkan.
Pencapaiannya di usia yang relatif muda (30 tahun) ini tak ayal membuat kita berdecak kagum. MAkin mengagumkan karena Angkie, finalis None Jakarta Barat 2008 dan penulis buku “‘Setinggi Langit”, adalah penyandang tuna rungu—kelompok yang masih kerap dipandang sebelah mata. Yang diberi pembekalan dan kemudian disalurkan ke perusahaan-perusahaan, juga adalah mereka yang memiliki keterbatasan seperti dirinya.
“Jujur dan menerima diri sendiri bahwa memiliki keterbatasan, itu yang terberat. Saya butuh sepuluh tahun untuk bisa seperti itu. Sampai sekarang pun kadang masih takut jika bertemu orang-orang baru. Takut, apakah mereka bisa menerima saya,” papar kelahiran Medan, 5 Juni 1987.
Tidak mudah menjadi penyandang disabilitas di Indonesia. Masyarakat, juga pemerintah, masih kurang mendukung difabel (penyandang disabilitas) untuk berkembang. Bahkan orang dengan difabel masih sering dianggap sebagai aib. Banyak yang keluarganya menutup-nutupi akses ke dunia luar, tidak boleh berkreasi. “Ini membuat mental kami drop. Kami manusia biasa seperti yang lain, hanya kurang di indera pendengaran,” ujar The Most Fearless Female Cosmopolitan 2008 ini.
Advokasi termasuk dalam ranah kerja Angkie. Ada Undang-Undang No.8/ 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan Perda No.10/2011, yang menyebutkan perusahaan harus mengalokasikan tenaga kerja minimal 2% untuk kaum disabilitas, sesuai kebutuhan. Kenyataannya, banyak perusahaan yang enggan menerapkan. Alasannya kadang dicari-cari: belum tahu ada peraturan seperti itu.
Angkie merasa ada penolakan saat bekerja di perusahaan, termasuk perusahaan di multi nasional, sampai ia di-PHK tanpa sebab yang jelas. Ini menjadi titik balik bagi Angki untuk membantu sesama penyandang tuna rungu. Ia putuskan mendirikan Thisable Enterprise saat berusia 25 tahun. “Mungkin ini maksud Tuhan membuat saya tuli. Banyak teman-teman yang harus diperjuangkan,” ujar ibu satu anak ini.
Malaria
Sakit malaria membuat badannya panas tinggi. Sejak usia 10 tahun itu secara bertahap ia mengalami penurunan pendengaran. Apakah memang karena malaria atau sebab lain, misal karena paparan antibiotik atau kina (obat malaria), dokter tak bisa menjelaskan. Di Ternate, Maluku Utara, ketika itu belum ada dokter spesialis THT (telinga hidung tenggorokan). Angkie mukim di Ternate karena ayahnya yang bekerja di BUMN (Badan Usaha Milik Negara) bertugas di sana.
Karena masalah pendengaran, Angkie tidak bisa merespon perkataan orang lain. Ia kerap dimarahi guru karena dianggap tidak mendengarkan. Dianggap ‘lemot’, perundungan dari teman sebaya menjadi ‘makanan’ Angkie sehari-hari.
“Saya sering pulang ke rumah dan menangis di kamar. Ibu menemani dan menenangkan,” kenangnya. “Orang normal tersinggung kalau dicaci maki. Pengidap difabel lebih sensitif. Jangankan verbal, lewat tatapan mata kami tahu kalau seseorang merasa tidak senang.”
Ia beruntung keluarga selalu melindungi dan tidak mengungkung. Sang ibu memberi dorongan agar ia bisa mengatasi masalah dan bisa hidup mandiri. Bungsu dari dua bersaudara ini berobat ke Jakarta dan menjalani tes audiologi. Saat itu gangguan dengar masih tergolong sedang, di kisaran 60 dB (desibel). Normalnya 0-20 dB. Kurang dengar ringan 21-40 dB, sedang 41-70 dB, berat 71-90 dB, tuli jika >90 dB.
Meski bolak-balik berobat bahkan sampai ke luar negeri, pendengarannya makin hilang. Ia berpikir lebih baik mati, ketika gangguan dengarnya di angka 120 dB. Angkie harus menggunakan alat bantu dengar (ABD). Pencerahan didapat dari seorang dokter, “Kamu harus menerima diri sendiri dengan segala keterbatasannya. Kalau tidak, akan makin sulit buatmu melangkah ke depan.” Ternyata, istri dokter itu penderita tuna rungu.
Saat kuliah, Angkie makin percaya diri. Ia memilih jurusan Komunikasi di London School of Public Relations, Jakarta, “Ibu sempat membawa saya ke psikolog gara-gara pilihan studi ini, hehehe.” Belum lulus S1, ia mendaftar ke jenjang S2. Ia ingin membuktikan dan tidak ingin orang melihat hanya dari sisi keterbatasan.
“Saya ingin melakukan personal branding. Saya mau orang melihat, Angkie yang tuna rungu ternyata memiliki sesuatu,” tukasnya. Dalam 5 tahun ia berhasil menyelesaikan program S1 sekaligus S2.
Kebahagiaan Angkie terasa lengkap dengan hadirnya Kayla Almahyra yang kini berusia 3 tahun. Angkie sungguh bersyukur, pendengaran putrinya normal. Menjadi ibu berkebutuhan khusus tentu merupakan tantangan tersendiri. Bagaimana kisahnya? Baca di sini. (jie-nid)