Maisuri T. Chalid, Universitas Hasanuddin
Ini adalah artikel kedua dalam seri tulisan dengan tema “Kesehatan Ibu dan Anak” dalam rangka memperingati Hari Kartini yang jatuh pada 21 April.
Pekan lalu publik dikejutkan oleh rencana perkawinan siswa sekolah menengah pertama (SMP), pasangan remaja berusia 15 tahun dan 14 tahun, di Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan. Walau Undang-Undang Perkawinan membatasi usia nikah laki-laki minimal 19 tahun dan perempuan 16 tahun, pengadilan agama di sana memenuhi permintaan dispensasi usia nikah kedua remaja itu untuk kawin.
Kejadian ini hanya satu dari maraknya perkawinan usia dini di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan 1 dari 4 anak perempuan di Indonesia telah menikah pada umur kurang dari 18 tahun pada 2008 hingga 2015.
Tercatat 1.348.886 anak perempuan telah menikah di bawah usia 18 tahun pada 2012. Bahkan setiap tahun, sekitar 300.000 anak perempuan di Indonesia, menikah di bawah usia 16 tahun. Tampaknya dalam kurun waktu 7 tahun sejak 2008 sampai 2015, hanya terjadi sedikit penurunan jumlah perkawinan usia dini di Indonesia. Karena usia di bawah 18 tahun masih digolongkan sebagai anak berarti perkawinan di bawah 18 tahun adalah perkawinan anak.
Tingginya perkawinan anak di Indonesia mencerminkan masih tingginya ketidaksetaraan gender. Indonesia memiliki Indeks Ketidaksetaraan Gender atau Gender Inequality Index (GII) pada 2015 sebesar 0,467 . Nilai GII adalah kisaran antara 0 sampai 1, 0 berarti ketidaksetaraan 0%, dan 1 artinya ketidaksetaraan 100%.
Lebih seabad sejak perjuangan Kartini untuk kesetaraan kaumnya, nilai GII Indonesia masih berada pada peringkat ke-105 dari 159 negara. Peringkat ini lebih rendah dari Cina (GII 0,164, peringkat ke-37) dan Filipina (GII 0,436, peringkat ke-96).
Indeks Ketidaksetaraan Gender mencerminkan ketidaksetaraan berbasis gender dalam tiga dimensi yakni kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan kegiatan ekonomi. Nilai GII yang tinggi, bahkan berkorelasi dengan tingginya angka kematian ibu di beberapa negara.
Perkawinan anak dan kematian ibu
Angka kematian ibu (AKI) di Indonesia, menurut Sensus Penduduk 2014, adalah 305 per 100.000 kelahiran hidup (bandingkan dengan AKI Malaysia 25,6 per 100.000 kelahiran hidup pada 2012). Bila dalam setahun jumlah ibu hamil di Indonesia sekitar 4,5–5 juta orang, dengan AKI 305 per 100.000 berarti setiap tahun ada sekitar 15.250 ibu yang meninggal di Indonesia karena kehamilan atau persalinannya. Jumlah ini sangat tinggi, bahkan tertinggi di antara negara-negara ASEAN.
Kematian ibu dilaporkan meningkat 2-4 kali lipat pada kehamilan usia dini dibandingkan dengan kehamilan di atas usia 20 tahun. Badan Pusat Statistik melaporkan pada 2016, sekitar 26,16% perempuan yang melahirkan anak pertama mereka berada pada usia di bawah 20 tahun. Dengan kata lain, lebih dari seperempat perempuan usia subur di Indonesia, melahirkan pada usia di bawah 20 tahun.
Mengapa perkawinan anak menjadi masalah serius? Perkawinan anak akan berujung pada kehamilan anak, yang selanjutnya, anak akan melahirkan anak. Kehamilan atau persalinan pada usia sangat dini akan berisiko si ibu mempunyai anak terlalu banyak dan jarak antara kehamilan yang terlalu dekat. Ini terjadi karena mereka memiliki masa usia subur yang lebih panjang dibandingkan bila mereka menikah pada usia dewasa. Terlalu muda, terlalu dekat, dan terlalu banyak merupakan “3 terlalu” dalam risiko kematian ibu.
Problem lain yang dihadapi oleh perkawinan usia dini dihubungkan dengan meningkatnya risiko komplikasi kehamilan yakni:
- Preeklamsia (hipertensi dalam kehamilan)
- Eklamsia (kejang pada kehamilan)
- Perdarahan pasca persalinan
- Persalinan macet (lama) dan keguguran (abortus).
Keempat faktor ini merupakan penyebab utama tingginya angka kematian ibu di Indonesia.
Tingginya angka perkawinan anak tidak terlepas dari rendahnya tingkat pendidikan, kemiskinan, norma sosial budaya dan keluarga didominasi oleh peran ayah. Norma itu, misalnya, pemahaman atau rasa malu jika anak perempuan mereka terlambat menikah atau menikahkan cepat untuk menghindari perzinahan.
Keterpurukan ini “difasilitasi” oleh regulasi negara yang tidak sensitif gender, yakni Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang membolehkan perempuan menikah pada usia 16 dan laki-laki pada usia 19 tahun. Kalau kurang dari usia itu, seperti kasus di Bantaeng, orang tua mempelai dapat meminta dispensasi umur nikah ke pengadilan dan tragisnya hakim mengabulkan.
Dengan melegalkan perkawinan anak perempuan 16 tahun, posisi perempuan dalam perkawinan (dengan segala implikasinya) di era digital ini hanya sedikit bergeser dari era Kartini, 118 tahun lalu. Kala itu, Kartini, yang menikah pada usia 24 tahun, meninggal tiba-tiba empat hari setelah melahirkan. Tidak ada catatan tentang penyebabnya, namun bila mencermati kronologis menjelang kematiannya, kemungkinan kematian itu disebabkan oleh preeklamsia. Saat ini, preeklamsia merupakan penyebab kematian ibu tertinggi di Indonesia. Bahkan seorang pejuang emansipasi harus berujung pada kematian ibu pasca melahirkan.
Risiko berlipat ganda nikah muda
Perempuan yang menikah sangat muda akan memiliki risiko perceraian yang lebih tinggi ketimbang yang menikah pada usia dewasa. Angka perceraian antara usia 20-24 tahun lebih tinggi pada yang menikah sebelum usia 18 tahun, dan cenderung meningkat dari tahun 2013-2015, baik di kota maupun di desa dan sering berakhir sebagai istri kedua atau ketiga, karena secara ekonomi mereka tidak mampu menghidupi anak-anaknya.
Ketidakberdayaan dan inferioritas perempuan dalam ekonomi akan menghalangi mereka untuk mendapatkan hak yang terbaik, bahkan untuk kesehatannya sendiri.
Anak perempuan yang telah menikah juga menghadapi masalah dalam pendidikannya. Mereka terpaksa putus sekolah karena peraturan sekolah tidak membolehkan mereka masuk ke ruang kelas. Lebih dari 90 persen perempuan usia 20-24 tahun yang pernah menikah (karena pernikahan dini) tidak lagi bersekolah. Situasi ini menambah lebar gap gender yang terjadi dalam hak untuk mendapatkan pendidikan.
Karena itu, pemerintah seharusnya serius mempertimbangkan isu-isu gender ketika mengeluarkan kebijakan kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak. Sayangnya, uji materi terhadap UU Perkawinan untuk menaikkan batasan usia nikah perempuan menjadi 18 tahun telah ditolak oleh Mahkamah Konsitusi.
![]() Budaya dan tradisi dalam masyarakat yang jelas merugikan kesehatan perempuan dan anak, tidak akan dapat diselesaikan tanpa intervensi regulasi yang sensitif gender.
Budaya dan tradisi dalam masyarakat yang jelas merugikan kesehatan perempuan dan anak, tidak akan dapat diselesaikan tanpa intervensi regulasi yang sensitif gender.
Maisuri T. Chalid, Lecturer and doctor, Departemen Obstetri Ginekologi, Universitas Hasanuddin
Sumber asli artikel ini dari The Conversation. Baca artikel sumber.
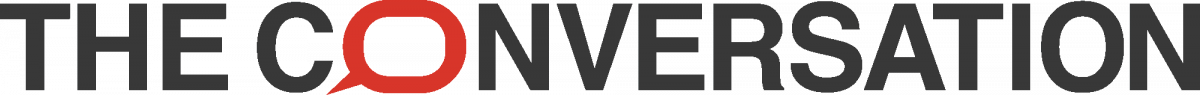
_______________________________
Ilustrasi: amyannbrockmeyer / Pixabay.com












