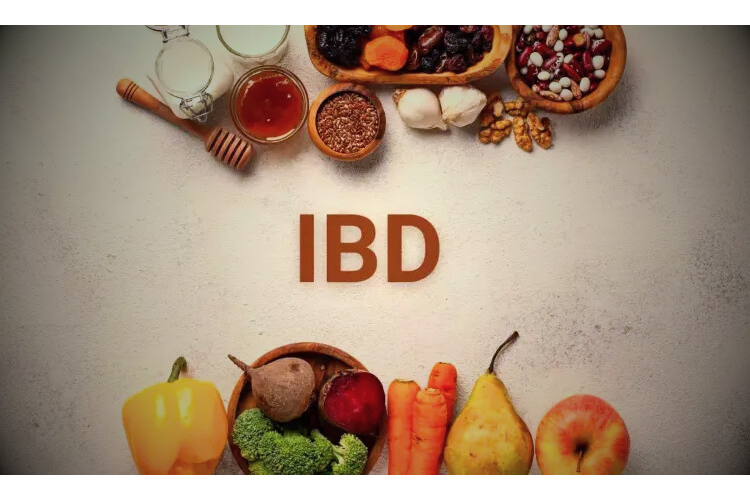Peter McCaffery, University of Aberdeen
Vitamin C adalah obat yang umum digunakan orang karena dipercayai mampu menyembuhkan flu biasa.
Meski ia membantu menjaga daya tahan tubuh kita, tidak ada bukti bahwa ia dapat mencegah atau mengurangi risiko terkena penyakit ini secara substansial.
Namun di tengah pandemi coronavirus jenis baru, beberapa “influencer” mengklaim bahwa mengkonsumsi vitamin C dalam dosis yang sangat tinggi dapat menyembuhkan COVID-19 (penyakit yang disebabkan oleh coronavirus baru tersebut).
Lalu, benarkah klaim bahwa vitamin C dapat menyembuhkan coronavirus?
Mempertimbangkan coronavirus terbaru ini masih berada di dalam kategori virus yang sama – yakni coronavirus – seperti flu biasa, maka tidak mungkin mengkonsumsi vitamin C akan mencegah atau menyembuhkan infeksi COVID-19.
Saya pernah menulis sebelumnya bahwa mengkonsumsi vitamin C untuk menyembuhkan flu biasa adalah gagasan yang dipopulerkan oleh kimiawan yang telah dua kali memenangkan Hadiah Nobel, Linus Pauling, dan kemudian dipromosikan oleh industri diet suplemen.
Sayangnya, sejak klaim Pauling tersebut pada 1970-an, nyaris tidak ada bukti pendukung.
Vitamin atau “vital-amines” pertama kali ditemukan pada awal abad ke-20 sebagai elemen yang hadir dalam kadar rendah di asupan kita sehari-hari dan berperan vital bagi kesehatan. Tentu, orang yang kekurangan vitamin tertentu akan mengalami penyakit.
Misalnya, orang yang kekurangan vitamin C akan terkena skorbut. Namun, baru pada awal 1930-an bahwa skorbut disebabkan oleh kurangnya vitamin C dalam tubuh, dan konsumsi vitamin dapat menyembuhkan kita dari penyakit tersebut.
Ilmu nutrisi lahir seiring dengan penemuan vitamin, dan telah berkembang sebagai industri yang kompetitif dan tanpa regulasi, yang kerap menawarkan “fakta ilmiah” yang tidak kalah saing dengan informasi palsu demi mengejar keuntungan finansial semata: pandemi coronavirus terbaru ini hanyalah contoh terbaru.
Artikel-artikel menyesatkan tersebut telah menyebar dengan cepat, dan kemungkinan menjadi penyebab kelangkaan pasokan vitamin C di Asia dan meningkatkan permintaan akan vitamin C dan multivitamin sebanyak lima kali lipat di Singapura.
Fungsi daya tahan tubuh
Vitamin C berperan penting dalam menjaga keseimbangan “redoks” dalam jaringan tubuh – ini adalah jenis reaksi dalam sel yang bertujuan menambah atau memindahkan oksigen, dan penting bagi banyak proses seperti menghasilkan energi bagi sel-sel tubuh.
Reaksi yang sama juga dapat menghasil produk yang berbahaya bagi tubuh – seperti spesies oksigen reaktif, yang bereaksi dengan lipid (lemak), protein, dan asam nukleat. Vitamin C dapat mengurangi reaksi berbahaya tersebut. Ia juga membantu enzim dalam membangun kolagen, yang diperlukan untuk menjaga jaringan tubuh kita.
Meski vitamin C tidak memiliki kemampuan ajaib untuk menyembuhkan penyakit, beberapa penelitian menunjukkan ia dapat membantu sistem daya tahan tubuh melawan bakteri dan virus.
Perannya dalam melawan infeksi viral baru-baru ini dimuat dalam sebuah kajian yang menemukan bahwa sel darah putih memerlukan vitamin C untuk menghasilkan protein dengan tujuan mengaktifkan sistem daya tahan tubuh melawan serangan virus.
Namun demikian, kita dapat dengan mudah mencukupi kebutuhan vitamin C dalam asupan kita sehari-hari sehingga sistem daya tahan tubuh kita tetap bekerja sepenuhnya. Vitamin C banyak ditemukan dalam berbagai buah dan sayuran, termasuk jeruk, brokoli, dan kentang.
Dan meski ia tidak beracun, tingginya daya larut vitamin C dalam air membuatnya juga mudah dikeluarkan dari tubuh, dosis berlebih dapat menyebabkan gejala-gejala yang membuat kita tidak nyaman seperti diare, mual, dan kram.
Walau saya mengatakan bahwa vitamin C tidak mungkin menjadi penyembuh COVID-19, fakta bahwa ia dapat meningkatkan sistem daya tahan tubuh kita bermakna bahwa mengatakan vitamin C sama sekali tidak ada gunanya adalah berlebihan.
Dan meski sebuah kajian menemukan bahwa vitamin C tidak berdampak dalam mengurangi frekuensi seseorang terkena flu biasa, ia juga menemukan bahwa bagi orang-orang biasa, ada penurunan kecil dalam durasi seseorang terkena gejala flu biasa.
Namun bagi mereka yang menjalankan kegiatan fisik berat dalam jangka singkat (seperti maraton dan ski), vitamin C mengurangi durasi dan tingkat keparahan akan risiko flu biasa mereka hingga separuh.
Efek kecil vitamin C terhadap coronavirus yang menyebabkan flu biasa telah membuka jalan bagi percobaan klinis baru yang bertujuan menyembuhkan infeksi COVID-19 dengan menggunakan vitamin C dalam dosis intravena yang sangat tinggi. Percobaan ini baru saja dimulai dan masih menunggu hasil.
Sebuah riset dari Shanghai Coronavirus Disease Clinical Treatment Expert Group menemukan bahwa mengkonsumsi vitamin C bisa melindungi seseorang dari “cytokine storm” atau produksi sel daya tahan tubuh yang berlebihan di paru-paru, akan tapi tanpa hasil dari uji klinis hal ini belum terbukti keampuhannya.
Penerapan vitamin C secara intravena (atau ke dalam pembuluh darah) akan menghasilkan kadar vitamin dalam darah yang jauh lebih tinggi dan cepat daripada konsumsi suplemen vitamin C secara oral.
Meski pendekatan ini dapat meningkatkan efek perlindungan vitamin C secara ringan, ini adalah skenario hipotetis dan injeksi intravena sendiri memiliki risiko, seperti infeksi, rusaknya pembuluh darah, emboli udara (atau terhalangnya pembuluh darah akibat keberadaan gelembung udara) atau penggumpalan darah.
Jadi meski vitamin C memiliki efek terhadap flu biasa dalam skala kecil, konsumsi suplemen vitamin C dalam takaran besar tidak akan mungkin menyembuhkan COVID-19 – atau berdampak besar sama sekali.
Bahkan jika vitamin C yang didapat secara intravena berfungsi untuk memperpendek durasi terjangkiti atau bahkan menyembuhkan COVID-19, ia hanya akan menjadi solusi sementara sebelum terapi yang menyerang virus itu sendiri, seperti vaksinasi, menggantikannya.
Cara yang paling efektif agar terhindar dari virus ini tetaplah mencuci tangan, tidak menyentuh mata, hidung atau mulut, dan menjaga jarak dengan seseorang yang menunjukkan gejala-gejala COVID-19.
Bram Adimas Wasito menerjemahkan artikel ini dari bahasa Inggris.
![]()
Peter McCaffery, Professor of Biochemistry, University of Aberdeen
Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.
![]()
_____________________________________________