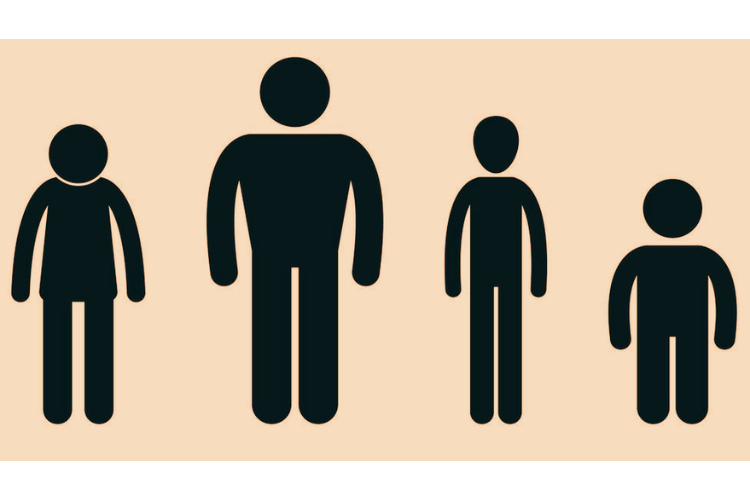“Jas merah – jangan sekali-kali lupakan sejarah”. Idiom ini lekat di telinga orang Indonesia, yang bermasud agar kita bisa belajar dari sejarah. Satu abad lalu (1918) terjadi pandemi flu (flu Spanyol) yang menyebabkan kematian 17-50 juta orang. Tercatat sebagai pandemi yang paling mematikan dalam sejarah. Apa yang bisa kita pelajari dari kejadian masa lampau sehubungan dengan penanganan wabah COVID-19?
Hidroklorokuin, obat antimalaria ini menjadi salah satu obat yang diandalkan untuk merawat pasien COVID-19. Di Indonesia, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) juga memasukkan klorokuin (chloroquine phosphate) dalam penanganan infeksi COVID-19 berat, atau yang disertai komplikasi.
Pemakaian klorokuin ini didasarkan pada percobaan skala kecil yang dilakukan oleh Prof. Didier Raoult, kepala institut rumah sakit universitas di Marseille, Perancis. Pada 16 Maret 2020, Ia mengumumkan timnya telah merawat 25 pasien COVID-19 dengan hidroklorokuin.
Setelah enam hari, hanya satu dari empat pasien yang masih memiliki virus dalam tubuh mereka, sedangkan 90% pasien yang tidak menggunakan obat itu masih terinfeksi. Di satu sisi, penelitian yang lebih besar tentang obat ini dan obat lainnya masih terus berlangsung.
Berkaca dari pandemi flu Spanyol, saat itu dokter di seluruh dunia meresepkan quinine (kina), jenis obat antimalarial lain, walau tidak ada bukti yang menyatakan bermanfaat untuk flu.
Menurut Laura Spinney, penulis Pale Rider : The Spanish Flu of 1918 and How it Changed the World, saat itu banyak dokter yang kurang memahami bagaimana interaksi obat malaria di dalam tubuh, tetapi mereka tetap meresepkannya. Menyebabkan pasien kerap mengalami efek samping seperti vertigo, tinnitus (telinga berdenging) dan muntah.
Mark Honigsbaum dalam buku Living with Enza, yang berisi pengalaman pribadinya saat terjadi pandemi flu tersebut di Inggris menjelaskan, warga London menolak ditipu dengan saran untuk berkumur dengan air asin, dan menuntut para dokter serta ahli kimia memberikan kina.
Dilansir dari the guardian, Laura Spinney menyatakan di saat krisis, bukan hanya politisi / pemerintah yang dipaksa membuat keputusan yang menabrak aturan. Di saat yang ideal, para ilmuwan akan memberikan fakta dan politisi akan membandingkannya menggunakan fakta lain sebelum membuat keputusan.
“Para politisi tersebut memikul beban etis. Tetapi saat ini kita tidak hidup dalam dunia yang ideal, sehingga pembagian kerja tersebut adalah ilusi,” katanya.
Dalam kondisi krisis ilmuwan jarang memiliki semua fakta (bukti). “Yang terbaik yang dapat mereka tawarkan adalah serangkaian kemungkinan hasil, dan kadang-kadang rentang itu begitu luas sehingga tidak berguna bagi pembuat kebijakan,” tutur David Kinney dari Santa Fe Institute, AS.
Dalam riset yang dilakukan Prof. Didier Raoult di Marseille, pasien COVID-19 dirawat menggunakan kombinasi obat hidroklorokuin dan antibiotik (azithromycin). Hidroklorokuin diketahui memiliki efek samping lebih ringan dibandingkan klorokuin. Sedangkan azithromycin biasa digunakan pada kasus pneumonia bakterial, komplikasi yang mungkin terjadi dari COVID-19.
Kombinasi ini dilaporkan aman pada kelompok pasien lain. Tetapi ada indikasi bila kombinasi tersebut memiliki efek samping pada jantung di beberapa pasien, sehingga sebelumnya para dokter memeriksa semua pasien dengan EKG (electrocardiogram).
Hingga saat ini, hasil pengujian pada 80 pasien telah dipublikasikan. Dilaporkan pengurangan jumlah virus (viral load) dan perbaikan gejala, dibandingkan pasien COVID-19 (yang dirawat di rumah sakit) di tempat lain.
Subyek yang terlalu sedikit
Jumlah subyek yang mendapatkan terapi kombinasi tersebut masih sangat sedikit menurut standard penelitian klinis, dan beberapa laporan menunjukkan inkonsistensi.
Para ahli lain mengkritik tidak adanya kelompok kontrol (pembanding) yang tepat. Tidak ada kelompok usia dan jenis kelamin yang sesuai yang menerima pengobatan dan dipantau dalam kondisi yang sama.
Prof. Didier mengatakan, “Akan tidak etis bahkan memiliki satu (subyek pembanding), saat mereka sedang berjuang untuk hidup mereka. Para staf medis juga mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan mereka, sementara tidak ada pilihan obat lain yang benar-benar efektif.”
Tetapi Prof. Didier juga mengetahui bahwa saat menyatakan keberhasilan metodenya tersebut, ia membuat keputusan berdasarkan etika, bukan bukti. Ia percaya waktu akan membuktikan bahwa ia benar.
Itu mungkin. Tetapi, menurut Laura, ketika Sir Arthur Newsholme, kepala medis dari dewan pemerintah daerah Inggris, membuat keputusan etis pada Agustus 1918, ternyata salah. Gelombang pandemi ringan yang pertama telah surut, dan perang dunia pertama memasuki fase terakhir.
Sir Arthur memutuskan untuk mengesampingkan rencana penanggulangan pandemi gelombang kedua yang sudah diprediksi, dan mengutamakan perang yang hampir selesai. Dalam beberapa minggu, pandemi flu yang lebih parah merebak.
“Politis dinilai oleh sejarah,” kata Prof. Didier. “Saya (dokter) akan dinilai oleh pasien-pasien saya.” Kita mungkin berpikir bila pemerintah dan ilmuwan tidak memberikan saran yang etis sepanjang krisis ini. Seperti anjuran untuk tetap tinggal di rumah – sebelum melakukan lock down di berbagai tempat- adalah setengah etis.
“Tetapi jika ilmuwan memiliki semua jawabannya, kita tidak akan berada di kondisi seperti ini saat ini,” tutup Laura. (jie)